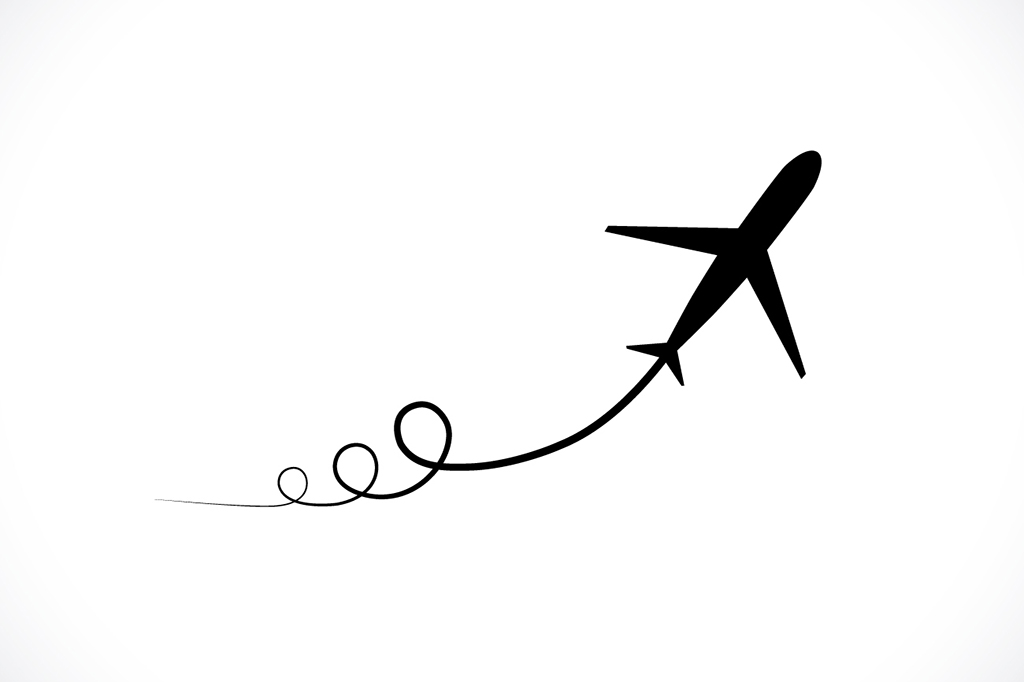Pesawat atau Kapai Po (Kapal Terbang), itulah sebutanku untuk benda yang terbang di langit mengangkut penumpang.
Usiaku saat itu masih delapan tahun. Usia ketika masih belum mengenal rumitnya masalah di zaman serba online seperti sekarang. Saat HP dan mainan elektronik bukan bagian penting yang ada di kepalaku.
Masa itu, aku menghabiskan waktu dengan teman hanya untuk bermain. Kami bermain patok lele, meu’en sye (engklek), meu’en layang, meu’en aneuk guli (kelereng), dan meu’en pet-pet (petak umpet).
Tak ada komputer, laptop, game online, mobile legend, PUBG seperti anak Android saat ini, yang masing-masing di tangannya punya HP bergenre smartphone dengan harganya jutaan atau semayam emas.
Waktu bermain biasanya kuhabiskan pada hari Minggu dengan kawan, tak mengenal waktu dan tempat. Permainan seperti itu cukup membuatku senang dan lalai hingga kerap kali mangkir dari jadwal mengaji.
Baca Juga: Pengusir Setan itu Bernama Ceudrie
Oke, kembali ke kapai po alias pesawat terbang.
Aku senang sekali jika melihat benda itu terbang di langit. Apalagi, jika langit kebetulan sedang cerah. Biasanya, ketika mendengar pesawat menderu, aku sering berhenti bermain untuk memastikan dari mana arah suara itu datang.
Aku tinggal di kampung yang amat jauh dari lapangan terbang. Sekarang, orang-orang sudah menyebutnya bandara atau bandar udara. Maka, pesawat adalah sebuah benda yang ajaib bagiku.
Bandara? Tentu lebih ajaib lagi.
Maka, kapan pun aku mendengar suara besar berdengung-dengung di langit, aku selalu memastikan, itu pesawat atau bukan?
Misalnya, satu kali saat bermain patok lele, ketika tiba giliranku, suara pesawat terdengar dari kejauhan. Lama-lama makin mendekati kampung kami.
Aku menunda memukul sebilah kayu kecil yang sudah kutaruh di lubang.
“Oi ka peh laju peu ka kalon u wateuh (Oi pukul terus jangan lihat ke atas),” teriak kawanku yang sudah pasang kuda-kuda untuk menangkap anak patok lele.
“Kapreh dilee, na kapai po, pat dilee? (Tunggu dulu, ada kapal terbang, tapi di mana?),” sahutku.
Tiba-tiba dari sebuah arah di atas langit, tampak moncong hitam dengan suara gaharnya melintas di atas kepalaku. Rasanya begitu dekat.
Perasaanku campur aduk; terkejut sekaligus senang melihat burung raksasa itu.
“Oi kapai-kapai ka eu keunoe (Oi pesawat lihat kemari),” teriakku sambil melambai tangan ke arah si pesawat. Kawan-kawanku tertawa walaupun mereka juga ikut berteriak-teriak nggak jelas.
Bertahun-tahun kemudian baru aku tahu, pesawat seperti itu sebutannya Hercules. Itu pesawat tentara.
Walaupun sudah memanggil-manggil, aku tahu pesawat itu tak akan menghiraukan teriakanku. Namun, aku senang melihatnya terbang di ruang yang tak pernah kusentuh dari tempat yang kupijak.
Nah, masih ada hubungannya dengan pesawat, nih, pemirsa. Waktu itu, pilot menjadi salah satu profesi yang masuk dalam daftar cita-cita para anak di kampungku.
Tanpa basa-basi, kalau ada anak ditanya besarnya mau jadi apa? Jawabannya pilot. Kenapa pilot, bukannya wartawan? Karena pilot bertugas mengendarai pesawat terbang.
Beberapa kawanku di sekolah bahkan menuliskan pada data diri di buku, di bagian cita-cita dengan kata-kata “Aku ingin jadi Pilot”. Keren bukan? Anak kampung, jauh dari bandara, sesekali lihat pesawat tapi bercita-cita menjadi pilot.
Sungguh besar imajinasi kami tentang masa depan, kan?
Ketika usia bertambah dan beberapa kawan sepermainanku meninggalkan kampung merantau ke tempat yang jauh, aku tak pernah berjumpa lagi dengan teman yang menulis pilot di lembar cita-citanya.
Entah ke mana perginya dia. Mungkin sudah menjadi pilot atau tidak, aku tak tahu. Yang pasti, aku masih senang melihat pesawat melintas di langit.
Semoga kawanku itu juga masih menyimpan kesenangan yang sama. Atau jika ia sudah jadi pilot, sesekali mau menengok ke bawah. Mana tahu masih ada anak-anak yang berteriak minta ditengok seperti kami dulu.
Diperbarui pada ( 3 Maret 2024 )